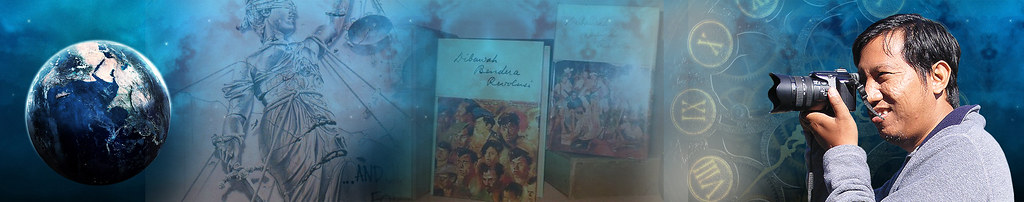EKONOM Kwik Kian Gie mengungkapkan, sebenarnya sejak kelahiran Bank Century (BC) sudah bermasalah beserta keseluruhan proses kerusakannya dibiarkan secara sistemik oleh BI. Sebagai bukti, Laporan Keuangan Bank Pikko dan Bank CIC, yang dinyatakan disclaimer oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), dijadikan dasar merger. Pemegang saham pengendali yang tidak memenuhi fit and proper test tetap dipertahankan. Pengurus bank, yaitu direksi dan komisaris, ditunjuk tanpa melalui fit and proper test.
Oleh karena kesulitan likuiditas
yang dihadapinya, BC mengajukan permohonan fasilitas pinjaman jangka pendek
(FPJP) kepada BI pada tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp 1 triliun. Permohonan
tersebut diulangi pada 3 November 2008. “Karena pada saat mengajukan permohonan
FPJP, posisi CAR BC menurut analisis BI adalah positif 2,35 % (posisi 30
September 2008), sedangkan persyaratan untuk memperoleh FPJP sesuai dengan PBI
No. 10/26/PB/2008 tentang FPJP Bank Umum, CAR-nya minimal harus 8 %, BC tidak
memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP,” katanya.