Ancaman hukuman terhadap anggota polisi yang terlibat kasus narkotika,
psikotropika dan bahan adiktif lainnya (narkoba), seolah tak pernah lepas dari
kontroversi ketika sudah sampai ke pengadilan. Seperti yang saat ini tengah hangat dibicarakan,
terkait keterlibatan salah seorang perwira polisi yang bertugas di Polwiltabes Surabaya, AKP.
Drs.Tulus Djunaedi, SH, yang hanya dituntut
10 bulan penjara oleh JPU. Bagaimana idealnya hukuman bagi para oknum
polisi yang seharusnya sebagai aparat penegak hukum, yang wajib memerangi
setiap bentuk kejahatan, termasuk peredaran narkoba, justru ikut
menyalahgunakannya? Apakah hal ini tidak justru memancing disparitas
(kesenjangan) pidana di masyarakat ?
DISPARITAS pidana mengandung arti perbedaan dalam pidana yang
dijatuhkan untuk berbagai kejahatan. Perbedaan dalam pidana ini sering terjadi
dalam proses penegakan hukum di Indonesia.
Sehingga acapkali penegakan hukum kita dinilai lebih bersifat diskriminatif,
inkosisten, tidak memakai parameter objektif dan mengedepankan kepentingan
kelompok tertentu.
Biasanya, dalam hal ini para
pelaku merasa membandingkan dengan orang yang sama sederajat pidananya dengan
dirinya. Kenapa jenis pidananya sama, tapi hukuman jauh lebih ringan, sedangkan
dirinya lebih berat. Pertanyaan itulah yang timbul di benak para terdakwa, yang
efeknya berimbas pada kehidupannya di lembaga pemasyarakatan (LP).
Sebagai contoh, pencurian
terhadap uang negara berjumlah miliaran rupiah dijatuhi pidana penjara 18
bulan, sedangkan pencurian sepasang sepatu dijatuhi pidana dua tahun penjara.
Contoh lain, bandar narkoba yang kedapatan membawa ratusan ekstasi dihukum 10
bulan, sedangkan yang bawa 2 butir ekstasi dikenai 2 tahun penjara. Kondisi ini
membuat publik mempertanyakan adakah kriteria dan parameter yang jelas bagi
hakim untuk menjatuhkan pidana selain pidana maksimum.
Guru Besar Fakultas Hukum
Universitas Indonesia
Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH., MA., PhD.,
mengatakan cukup wajar jika akhirnya publik mempertanyakan. Apakah hakim
telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan? Dari
sisi sosiologis, mengingat dalam kondisi disparitas pidana dipersepsi publik
sebagai bukti ketiadaan keadilan (social
justice).
Namun, Secara yuridis formal,
kondisi ini tidak dapat dianggap melanggar hukum, karena, (a) undang-undang
hanya menentukan pidana maksimum, (b) adanya kebebasan hakim yang merupakan
salah satu pilar dari ”negara hukum”, dan (c) setiap kasus memiliki
karakteristik masing-masing yang tidak mungkin disamakan.
Pertanyaan lanjutannya, apakah
undang-undang yang dibuat melalui proses legislasi telah menunjukkan
proporsionalitas antara kejahatan yang dilakukan dengan pidana yang diancamkan,
antara satu kejahatan dengan kejahatan lain. Pasalnya, baik KUHP yang merupakan
warisan Belanda, maupun undang-undang yang dihasilkan DPR selama ini juga tidak
dilandasi pada satu perangkat parameter yang konkret dalam menentukan ancaman
pidana.
Pertanyan ini harus mulai dijawab
dari makna pidana dan konsep pemidanaan itu sendiri, apakah ia dijatuhkan
semata sebagai harga yang harus dibayar pelaku kejahatan semata, ataukah harus
memiliki tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pelakunya. Seharusnya,
jawaban akan falsafah pemidanaan tersirat dalam criminal policy.
Cukup ironis, karena sejarah
pemidanaan di Indonesia
menunjukkan bahwa kitab-kitab hukum kuno sudah menyiratkan falsafah pemidanaan,
yang intinya pidana merupakan harga yang harus dibayar pelaku kejahatan, namun
sekaligus harus punya tujuan yang lebih besar untuk masyarakat dan pelaku.
Betapapun sulitnya hal ini dilakukan, karenanya, sudah masanya Indonesia
memilih falsafah pemidanaan yang merupakan kompromi dan kumulasi pandangan yang
ada dalam masyarakat yang heterogen ini, di sinilah peran legislatif menjadi
sangat menentukan.
Transformasi pendidikan
Dalam proses penegakan hukum
selalu ada unsur trasnformasi pendidikan. Karenanya, dengan adanya disparitas
pidana sebenarnya menghilangkan unsur tadi, sehingga tidak jelas, mana yang
harus dipilih, Karena itu Pakar Hukum Universitas 17 Agustus 45 (Untag) Krist L.
Leiden, menganjurkan proses penegakan hukum itu ahrus selalu ada proses untuk
mengarah ke transformasi pendidikan.
Dengan tranformasi pendidikan ini
mengandung arti penegakan hukum harus mempunyai unsur pendidikan terhadap
masyarakat. Oleh karenanya, setiap aparat penegak hukum harus sadar, apa yang
dilakukannya itu mempunyai konsekuensi sosial. Mengingat, tindakannya itu
nantinya akan diperhatikan dan di contoh masyarakat.
Kirst mengakui secara normatif
hakim dan JPU mengikuti aturan yang ada dalam tuntutan tersebut. Namun,
sebaiknya hakim harus melihat secara proporsional terhadap sanksi pidana yang
akan diberikannya. Pertama, sebagai bagian dari aparatur negara, AKP Tulus
harusnya memberikan contoh yang baik di masyarakat. Kedua, vonis berat
setidaknya memberikan efek jera kepada setiap orang termasuk aparat yang
menyalahgunakan jabatannya.
Jadi, dalam kasus ini, hakim
harus menekankan pada keadilan sosial dan unsur transformasi pendidikannya.
“Hukuman maksimal harus diterapkan agar
jangan sampai terjadi disparitas pidana,” tegas Krist.
Hal senada diungkapkan pula oleh
Dewan Penasehat DPD Granat Jatim, Singky Soewadji. Menurutnya hukum itu tidak
mengenal status dan jabatan seseorang. Siapa pun sama dimata hukum. Begitu pun
penegak hukum yang melanggar hukum harus dihukum, sama seperti masyarakat
lainnya. Pasalnya, hukum Indonesia
juga mengatur persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum (equality before the law). Dengan demikian
siapapun orangnya, tak peduli apa pekerjaannya, harus mendapat perlakuan sama
di muka hukum. “Bahkan kalau perlu, hukumannya harus lebih berat. Dan institusi
kepolisian harusnya legowo. Mereka
itu kan
aparat yang semestinya mencegah, kok malah ikut melibatkan diri,” katanya.
Bahkan Singky menegaskan
sebaiknya oknum-oknum polisi itu diancam dengan hukuman yang lebih berat.
“Kalau perlu hukuman mati,” tegasnya. semestinya sebagai penegak hukum, apa
yang telah dilakukan oleh oknum-oknum polisi itu diancam dengan hukuman yang
lebih berat. Bahkan kalau perlu diancam hukuman mati.
Tujuannya, untuk memberikan efek
jera yang kuat bagi polisi dan warga lainnya. Akan lebih sempurna jika
pemberlakuan hukuman lebih berat tidak hanya dibebankan kepada polisi, tetapi
juga aparat hukum lain yang juga terlibat narkoba, seperti jaksa dan hakim.
“Logikanya begini. Polisi yang
sering disebut sebagai ujung tombak penegakan hukum, seharusnya mempunyai
kepatuhan hukum yang lebih baik daripada warga lainnya,” ujarnya.
Ditambahkannya, sebagai aparat
hukum, polisi memiliki empat sikap dasar di bidang hukum, yang diajarkan saat
menempuh pendidikan kepolisian. Pertama,
memahami hukum. Kedua, mampu
menerapkan hukum. Ketiga, mematuhi
hukum. Dan yang keempat, siap
ditindak atau diberi sanksi jika ia melanggar hukum. Dengan demikian, jika
mereka melanggar hukum, sudah selayaknya dihukum lebih berat daripada hukuman
terhadap masyarakat pada umumnya.
Namun seruan moral ini, akan
sangat tidak berarti bila tak mendapatkan dukungan dari institusi tempat dimana
sang oknum ini berada. "Sebab dalam langkah teknisnya, akan sangat
tergantung kepada Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah Red) masing-masing,"
jelasnya. ri/ru
Dimuat di Harian Surabaya Pagi, 29/9/2005
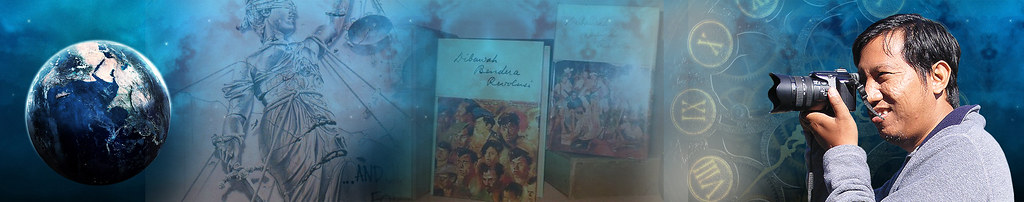
1 komentar:
kalau boleh tau, kasus siapa yang bandar narkoba yang kedapatan membawa ratusan ekstasi dihukum 10 bulan, sedangkan yang bawa 2 butir ekstasi dikenai 2 tahun penjara itu? terima kasih
Posting Komentar